Fenomena Laki-Laki Kawin Lebih dari Satu: Antara Nafsu, Budaya, dan Kekuasaan, dan Dampak Sosial
Fenomena laki-laki yang menikahi lebih dari satu perempuan bukan hal baru. Dari zaman kerajaan, kolonial, hingga era modern, poligami muncul di berbagai lapisan masyarakat. Fenomena ini tidak hanya terjadi pada rakyat biasa, tetapi juga sering melibatkan pejabat, tokoh publik, dan wakil rakyat yang seharusnya memberi teladan.
Pertanyaannya: apa yang mendorong laki-laki kawin lebih dari satu? Apakah sekadar dorongan biologis, budaya, kuasa sosial, atau kombinasi semuanya? Dalam artikel ini, kita akan mengupasnya dari berbagai sisi, termasuk sejarah, psikologi, sosial, hukum, dan refleksi modern.
1. Dorongan Biologis dan Nafsu
Secara biologis, sebagian laki-laki memiliki dorongan seksual lebih besar dibanding perempuan. Teori evolusi menyebut laki-laki terdorong memperbanyak keturunan demi melanjutkan garis keturunan. Dalam sejarah, raja-raja dan bangsawan sering memiliki banyak istri untuk menjaga kelangsungan dinasti.
Namun di era modern, dorongan biologis sering hanya menjadi alasan permukaan. Dorongan sesungguhnya lebih terkait nafsu, ego, dan kontrol diri yang lemah. Faktor psikologis seperti rasa percaya diri berlebihan, ambisi sosial, dan kebutuhan pengakuan publik turut memicu fenomena ini.
Beberapa penelitian psikologi menunjukkan bahwa laki-laki dengan kontrol diri rendah cenderung lebih mudah mencari pasangan tambahan meskipun sudah menikah. Dengan kata lain, kawin lebih dari satu bukan hanya soal biologi, tetapi juga keinginan pribadi, gengsi, dan dominasi sosial.
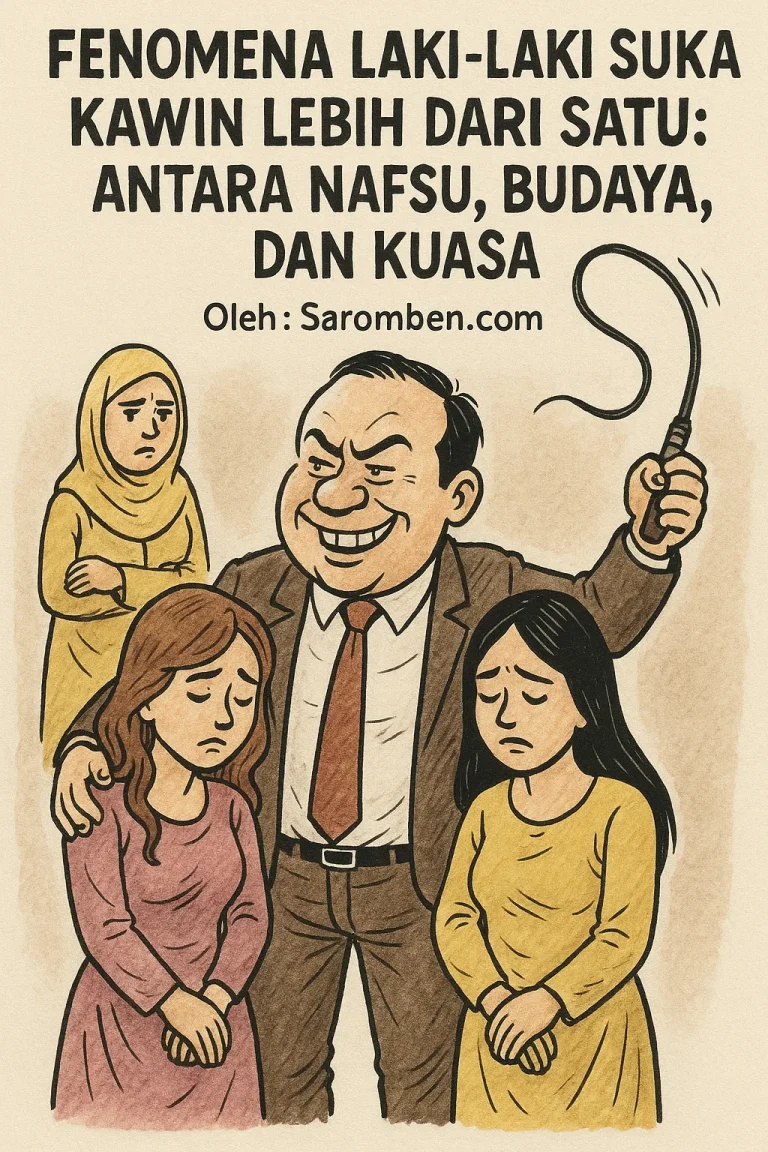
Baca Juga: Peran LSM dan Wartawan dalam Menjaga Transparansi Publik di Era Digital
2. Legitimasi Budaya dan Agama
Dalam banyak budaya dan agama, poligami diberikan legitimasi tertentu. Dalam Islam, seorang laki-laki boleh menikahi hingga empat istri dengan syarat mampu berlaku adil. Namun kenyataannya, praktik poligami sering menyimpang dari prinsip keadilan.
Di Indonesia, poligami masih menjadi isu kontroversial, terutama di kalangan pejabat dan selebriti. Seringkali poligami dilakukan atas dasar gengsi, nafsu, atau status sosial, bukan keadilan terhadap pasangan. Istri pertama sering menjadi pihak yang dirugikan, baik secara emosional maupun ekonomi.
Beberapa suku di Indonesia menganggap poligami sebagai simbol tradisi dan kemapanan. Menambah jumlah istri dianggap meningkatkan prestise, sehingga menimbulkan tekanan sosial bagi laki-laki untuk mengikuti norma budaya tersebut.
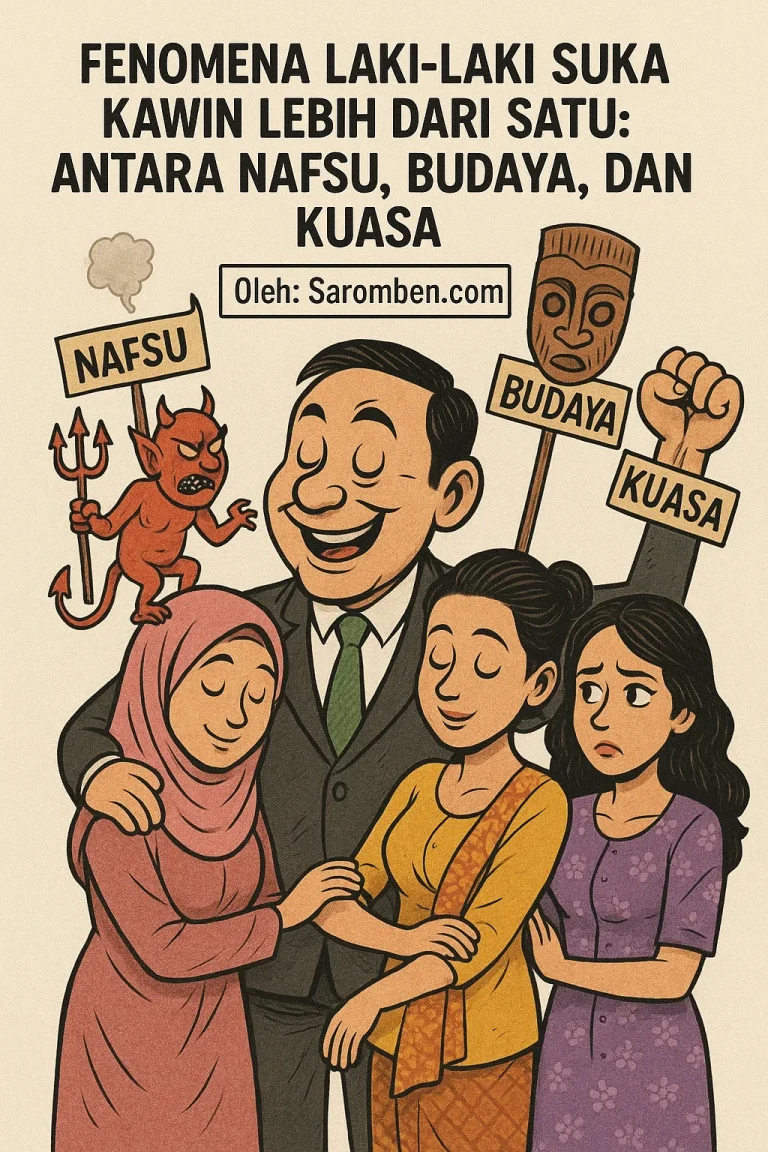
Baca Juga: PPP di Persimpangan Sejarah: Bisa Bangkit di Era Digital atau Tenggelam?
3. Sejarah Poligami dari Kerajaan hingga Modern
Sejarah mencatat bahwa poligami tidak hanya sekadar budaya, tapi juga alat politik. Raja-raja di Nusantara dan Asia sering menikahi banyak istri untuk membentuk aliansi politik. Misalnya, raja Majapahit memiliki beberapa permaisuri dan selir untuk menjaga stabilitas kekuasaan.
Di era kolonial, poligami tetap dipraktikkan, terutama di kalangan elite dan pejabat yang meniru pola kerajaan. Saat ini, poligami modern muncul tidak lagi untuk politik, tapi lebih pada gengsi sosial, kekuasaan ekonomi, dan pengakuan publik.
4. Gengsi, Status, dan Kekuasaan
Poligami sering dianggap simbol prestise. Semakin banyak istri, semakin tinggi status sosial dan pengaruh yang dimiliki. Fenomena ini lebih sering muncul di kalangan elite politik, pejabat publik, dan tokoh masyarakat.
Masyarakat kerap lebih sibuk membicarakan jumlah istri seorang pejabat daripada mengawasi kinerja dan integritasnya. Dalam konteks kekuasaan, poligami menjadi alat dominasi: laki-laki menunjukkan kemampuan finansial, kontrol sosial, dan kekuatan budaya.
Contoh nyata terlihat pada beberapa tokoh publik yang menambah istri untuk menunjukkan kemampuan ekonomi dan sosial. Fenomena ini memunculkan kontradiksi antara moralitas, budaya, dan gengsi sosial.
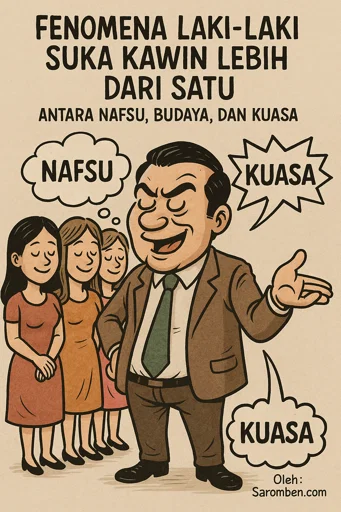
Baca Juga: Sejarah Runtuhnya Majapahit: Pelajaran Berharga bagi Komunitas, Ormas, dan LSM
5. Dampak Psikologis pada Perempuan dan Anak
Fenomena kawin lebih dari satu jarang menguntungkan perempuan. Istri pertama dan berikutnya kerap menjadi korban senyap: kehilangan perhatian, tersisih, tekanan emosional, hingga stres berat.
Anak-anak juga merasakan dampak psikologis: rasa tidak aman, persaingan antar saudara, hingga masalah perilaku. Studi menunjukkan bahwa anak-anak dalam keluarga poligami sering mengalami kesulitan membangun hubungan sehat di masa dewasa.
Psikolog keluarga menyarankan pendampingan untuk perempuan dan anak agar trauma dapat diminimalkan. Terlebih, dampak ekonomi juga nyata: pembagian aset, biaya hidup, dan pendidikan anak menjadi tantangan bagi keluarga poligami.
Baca Juga: Mengapa Orang Suka Menghasut? Ternyata Ini Alasannya
6. Perspektif Sosial dan Gender
Fenomena ini mencerminkan kultur patriarki yang masih kuat. Poligami bukan hanya persoalan individu, tetapi juga cermin ketimpangan sosial dan gender.
Selama masyarakat menoleransi poligami atas dasar gengsi dan kuasa, perempuan tetap berada dalam posisi rentan. Kesetaraan gender dan kesadaran sosial menjadi kunci untuk mengurangi praktik poligami yang merugikan.
Kemampuan sejati seorang laki-laki tidak diukur dari jumlah istri, tetapi sejauh mana ia mampu adil, bertanggung jawab, dan setia pada komitmen.
7. Dampak Sosial dan Ekonomi
Poligami tidak hanya berdampak pada keluarga, tapi juga pada masyarakat luas. Secara ekonomi, poligami menuntut biaya hidup lebih tinggi. Keluarga dengan penghasilan terbatas kerap menghadapi konflik karena ketidakmampuan memenuhi kebutuhan semua anggota.
Secara sosial, poligami dapat menimbulkan stigma, perpecahan sosial, atau bahkan persaingan keluarga. Hal ini tercermin dalam fenomena masyarakat yang membicarakan kehidupan pribadi elite dibandingkan menilai kinerjanya secara objektif.
8. Poligami Modern: Hukum dan Tantangan
Di era modern, poligami menghadapi tantangan hukum dan sosial. Beberapa negara membatasi jumlah istri, sementara lembaga sosial menekankan pentingnya persetujuan, keadilan, dan tanggung jawab dalam pernikahan.
Di Indonesia, poligami diatur oleh UU Perkawinan. Beberapa pengadilan menolak permohonan poligami jika dianggap merugikan istri atau anak. Kesadaran hukum dan sosial harus berjalan seiring untuk mengurangi praktik yang merugikan pihak tertentu.
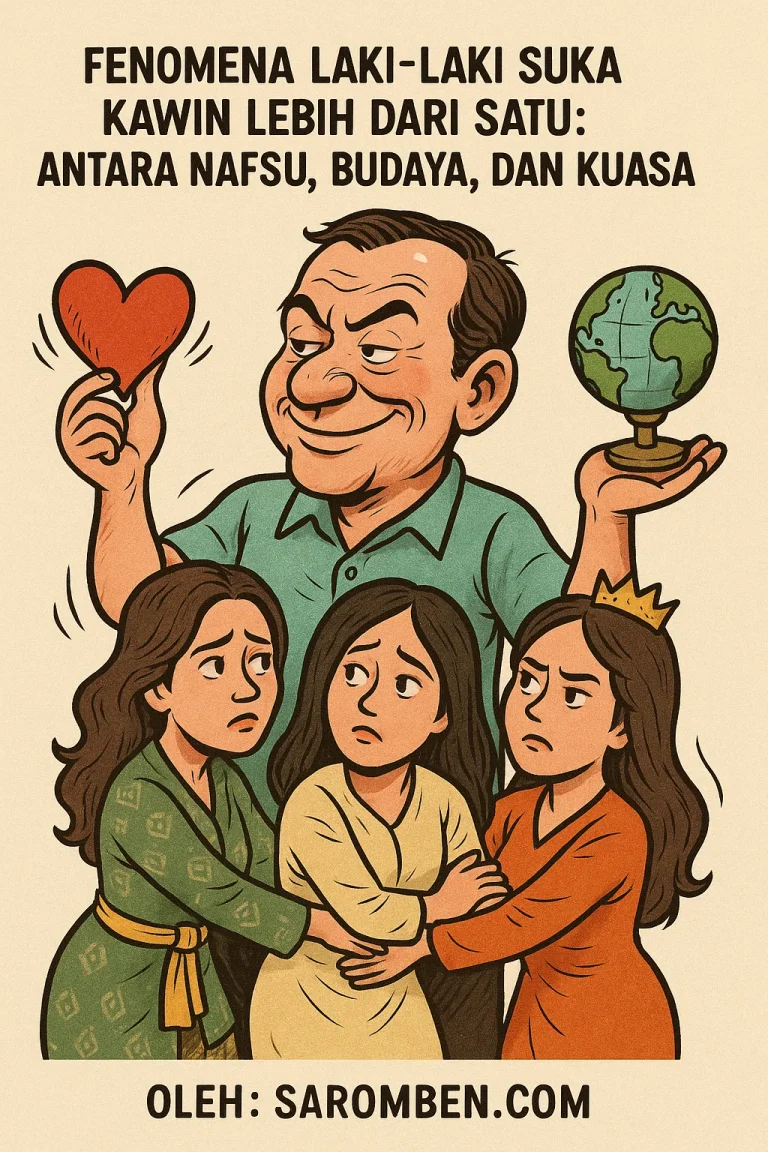
Baca Juga: DLH Melawi, Penggerak Utama Pelestarian Alam Lokal
9. Solusi dan Alternatif
Solusi praktis menghadapi poligami:
1. Edukasi Kesetaraan Gender: Memahami hak perempuan dan dampak psikologis poligami.
2. Literasi Agama: Memahami prinsip adil dalam poligami.
3. Pendampingan Psikologis: Untuk istri dan anak agar trauma dapat diminimalkan.
4. Pengawasan Hukum: Menegakkan UU Perkawinan agar poligami tidak merugikan pihak tertentu.
5. Perubahan Budaya: Menggeser pandangan masyarakat dari gengsi sosial ke tanggung jawab keluarga.
Solusi ini tidak hanya mengurangi praktik poligami yang merugikan, tetapi juga memperkuat kualitas hubungan dan kesejahteraan keluarga.
10. Refleksi Akhir
Fenomena laki-laki kawin lebih dari satu menyimpan banyak pelajaran. Poligami atas dasar nafsu dan gengsi mencerminkan kegagalan pengendalian diri dan budaya patriarki. Sebaliknya, laki-laki yang mampu menjaga komitmen, adil, dan bertanggung jawab adalah simbol kejayaan sejati dalam kehidupan rumah tangga.
Masyarakat modern perlu menilai pernikahan bukan dari jumlah pasangan, tetapi dari kualitas hubungan, keadilan, dan keberlangsungan keluarga. Dengan perspektif ini, poligami dapat dijalankan dengan kesadaran moral, tanggung jawab, dan adil terhadap semua pihak.
Catatan Penting
Tidak semua wanita setuju dengan poligami; banyak juga yang menolak karena pertimbangan emosional, psikologis, atau prinsip kesetaraan.
Poligami yang dijalankan tanpa keadilan atau persetujuan semua pihak sering menimbulkan konflik keluarga dan trauma psikologis.













